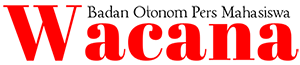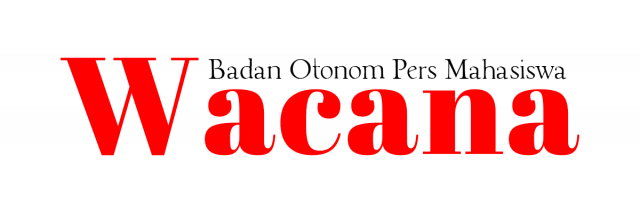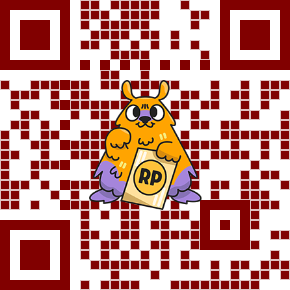Oleh: Monalisa
Program lumbung pangan alias food estate terkesan buru-buru. Berpotensi buruk untuk iklim dan terbukti banyak gagalnya.
Pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya bahas isu swasembada pangan. Baru-baru ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebut akan buka 20 juta ha hutan. Pernyataan itu jadi kontroversi. Katanya, lahan itu salah satunya buat swasembada pangan, selain untuk energi.
Pada sebuah berita yang ditulis oleh Arrijal Rachman dari CNBC Indonesia, dikatakan bahwa Prabowo Subianto akan memindahkan food estate, program unggulan swasembada pangan, dari Kalimantan ke Papua. Alasan utamanya karena tanah di Kalimantan kurang subur.
Program food estate di Kalimantan Tengah ini merupakan program Joko Widodo. Pada awalnya, program lumbung pangan ini dilakukan sebagai respons dari Presiden Joko Widodo untuk menangani ancaman paceklik, kekeringan, dan peristiwa pandemi COVID-19.
Sejumlah daerah di Indonesia ditargetkan untuk melaksanakan program ini, di antaranya: Kalimantan Tengah, NTT, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benak saya ketika saya membaca berita tentang food estate ini dan akan saya jabarkan satu per satu.
Di tengah krisis iklim, apakah food estate menjadi urgent?
Perlu diketahui, pembukaan lahan yang masif untuk program ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan alam. Krisis iklim yang terjadi di dunia; gelombang panas, badai, hujan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya.
Pembukaan lahan yang besar untuk menjalankan program ini juga melepaskan gas karbon dengan jumlah yang masif. Deforestation yang terjadi juga menyebabkan hilangnya “tempat penyimpanan” gas karbon di bumi.
Tentu kita pernah belajar bagaimana fotosintesis terjadi pada saat di bangku sekolah. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan memproduksi oksigen.
Dengan pemahaman tersebut, yang jadi pertanyaan apakah mengorbankan wilayah yang sebesar itu merupakan trade off yang seimbang dengan dampak iklim yang terjadi? Tentu nantinya program ini akan menghasilkan untuk kebutuhan pangan umat manusia, khususnya rakyat Indonesia.
Terus apa? Setelahnya bagaimana? Karena kerusakannya sudah terjadi lebih dulu. Mitigasi terhadap dampak iklimnya bagaimana? Apakah ada pemerintah mempertimbangkan hal ini?
Sepanjang saya menulis ini, saya belum melihat usaha pemerintah untuk mencari cara untuk mengatasi risiko iklim yang justru menjadi penghalang terbesar untuk program food estate.
Jika pemerintah memberikan klaim bahwa krisis iklim menjadi masalah untuk panen, lalu mengapa pemerintah melaksanakan program ini yang justru menjadi kontributor besar untuk permasalahan iklim? Jadi bagaimana?
Jika dilihat dari perspektif ini, nampaknya justru program lumbung pangan ini menjadi mekanisme gali lubang tutup lubang. Ujungnya sama saja.
Banyak gagalnya, kenapa masih dilanjut?
Pada salah satu berita yang penulis baca tentang program lumbung pangan yang dilaksanakan di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, dikabarkan bahwa proyek ini gagal dan ditinggalkan begitu saja, alias mangkrak.
Gagal panen terjadi padahal lahan sudah dibuka lebar-lebar. Pembukaan lahan bukanlah usaha yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, ada dana dengan jumlah besar yang dikerahkan untuk buka lahan saja.
Apakah ini tidak menggelitik pikiran Anda untuk berpikir? Apakah tidak terlintas di pikiran Anda tentang apa yang ada di dalam kepala para pemerintah ketika mereka melaksanakan program ini?
Apakah mereka tidak memikirkan hal-hal seperti mitigasi risikonya, atau memperhitungkan cost & benefit yang akan didapatkan dari program ini, atau hal-hal lainnya yang seharusnya dipikirkan sebelum melaksanakan sebuah program yang ditujukan untuk orang banyak?
Jika pemerintah berdalih dengan alasan-alasan klise seperti: untuk diversifikasi pangan, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan inovasi untuk pertanian, dan lain sebagainya, jujur saja melihat dari track record program ini, rasanya alasan-alasan tersebut hanya sekadar jargon belaka.
Sekarang melihat pelaksanaan program ini, rasa-rasanya lumbung pangan yang seharusnya jadi program untuk menyejahterakan rakyat sepertinya jadi program untuk menyejahterakan mereka yang bermain di belakang layar.
Mereka yang menjadi stakeholder untuk menjadi pelaksana teknis sebuah program karena nanti ada persenan yang masuk ke kantong mereka, mereka yang menjadi pion-pionnya kecipratan proyek 2M (makasih, mbak/mas).
Gagal panen, lahan tak subur, buka lahan baru jawabannya!
Aneh. Satu pertanyaan, apakah sudah pernah ada track record kalau program ini benar-benar menghasilkan? Tapi perlu dipahami, dengan lahan yang dibuka sekian ribu hektar, apakah lahan tersebut benar-benar dimaksimalkan potensinya?
Apa yang dihasilkan oleh program ini yang memang secara langsung dirasakan oleh masyarakat secara holistik? Tidak hanya diversifikasi pangan yang terjadi, tetapi ada kestabilan antara supply and demand, misalnya.
Atau ada dampak baik yang dirasakan oleh petani atau apa saja yang bisa menjadi titik terang untuk menyatakan bahwa program ini berhasil dari awal perencanaan hingga akhirnya masa panen. Apakah ada? Jika ada, di mana? Kapan terjadinya? Bagaimana keberhasilannya? Apa hasilnya?
Pada sebuah berita online yang diterbitkan oleh Kompas pada 30 Oktober 2024 dengan judul “Proyek Food Estate Berlanjut di Pemerintahan Prabowo, Walhi: Warisan Buruk Pemerintahan Jokowi”, tertulis bahwa Amran mengatakan mereka ingin melanjutkan apa yang sudah dirintis. Menurut Amran, yang di Kalimantan sedang diperbaiki.
Pertanyaannya, kalau memang sedang diperbaiki, apa urgency-nya untuk memiliki rencana pemindahan program ini ke Papua? Kalau memang sedang diperbaiki, bagaimana usaha perbaikannya dilakukan?
Kalau memang sedang diperbaiki, berapa tinggi kemungkinan lahan tersebut untuk bisa menjadi lahan layak pakai? Kalau memang sedang diperbaiki, kenapa baru sekarang? Dan kenapa diperbaiki? Memangnya kemarin kenapa? Aneh, gak sih?
Jadi, kesimpulannya?
Setelah melihat segala huru-hara program lumbung pangan ini, saya berpendapat bahwa program ini merupakan sebuah program yang dijalankan secara terburu-buru dan tanpa perhitungan.
Sebuah kebijakan yang seharusnya menjadi jawaban untuk permasalahan yang kritikal bagi rakyat Indonesia, nampaknya menjadi sebuah bumerang.
Mereka yang menjadi pelaksana teknis program ini mungkin tidak merasakannya, atau mungkin mereka merasakannya tetapi tidak peduli, atau mungkin mereka merasakan dan peduli tetapi tidak bisa berbuat banyak. Only God knows why.
Jika dikatakan bahwa alasan program ini dijalankan karena ingin melakukan tindakan preventif terhadap krisis iklim dan gagal panen; dari proses mulai buka lahannya saja program ini sudah menambah kerusakan iklimnya, artinya probabilitas gagal panen akan semakin tinggi.
Jika dikatakan bahwa alasan program ini dijalankan karena ingin meningkatkan diversifikasi pangan; setiap tanaman pangan punya kriteria khusus yang harus dipenuhi agar bisa tumbuh dan nantinya dipanen.
Tetapi pada praktiknya, pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini. Mungkin dipikirnya semua tanah bisa ditanam semua jenis tanaman pangan. Padahal, kan, tidak begitu.
Program ini juga tidak melibatkan para ahli yang akhirnya tindakan ini dijalankan sepihak karena maunya pemerintah.
Langsung buka lahan besar tanpa memperhitungkan aspek lainnya yang saling berkaitan seperti pengetahuan masyarakat terhadap pertanian, inovasi, dan alamnya itu sendiri. Semua dijalankan seakan bisa disulap dalam semalam dan, bam, tumbuh dan panen.
Program yang dijalankan dengan tergesa-gesa, ditambah dengan mekanisme cacat yang kurang perhitungan, ditambah dengan kerusakan sebelumnya yang terjadi secara berkelanjutan membuat program ini tidak akan pernah berhasil pada akhirnya.
Tidak semua yang sudah dirintis harus dilanjutkan. Jika yang dirintis tidak menghasilkan atau lebih buruknya malah membawa kerusakan, lebih baik dihentikan saja. Saya yakin pemerintah memiliki kapasitas untuk mencari alternatif lain dalam mengatasi kelangkaan pangan yang mungkin terjadi karena krisis iklim ini.
Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah mau untuk melakukannya?
*****
Penulis merupakan alumni Antropologi Sosial FISIP USU, stambuk 2020. Tulisan dimuat lewat program kontribusi.