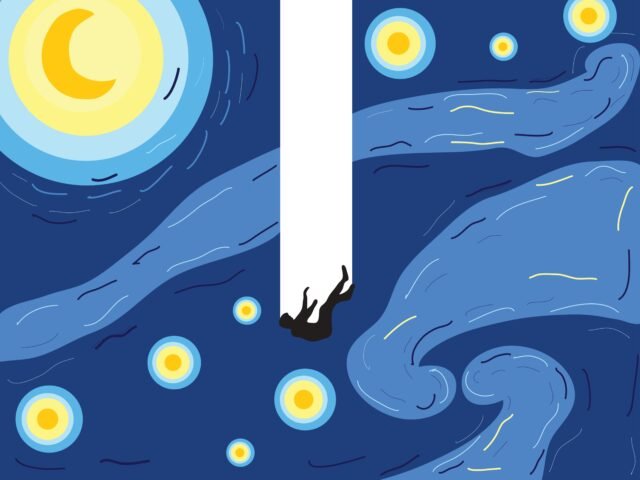
Oleh: Rachel Caroline L.Toruan, Mila Audia Putri
“Permisi bu, saya ingin mendaftarkan teman saya yang membutuhkan layanan konseling di sini, tapi dia ga berani untuk mendaftarkan sendiri. Pendaftarannya gimana ya, bu?”
Suara dari sudut ruangan itu sontak memecah keheningan di Poliklinik Universitas Sumatera Utara (USU). Salah seorang mahasiswa memberanikan diri untuk menanyakan prosedur pendaftaran konseling bagi temannya, sebab ia tahu, kampusnya menyediakan fasilitas konseling bagi mahasiswa.
Secara seksama mendengar keterangan pegawai poliklinik yang memaparkan mekanisme pendaftaran layanan konseling di USU–bahwasanya pendaftaran konseling dapat dilakukan melalui narahubung di WhatsApp.
Barangkali dia paham benar bahwa temannya sedang mengalami pergumulan dan butuh pertolongan. Memang, seiring bertambahnya usia, tak jarang individu merasakan kompleksitas kehidupan dalam menghadapi permasalahannya. Hal inilah yang membuat pembahasan mengenai kesehatan mental banyak digaungkan, dengan harapan dapat menunjukkan kepedulian kepada sesama untuk meningkatkan kesejahteraan individu.
Kesehatan mental seperti apa yang seharusnya kita tunaikan? Sebagaimana yang dijelaskan World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah keadaan individu yang mampu mengatasi tekanan hidup dan menyadari penuh tentang potensi diri mereka yang sebenarnya.
Topik kesehatan mental kini masih berhasil mencuri perhatian; senantiasa segar di ingatan dan perbincangan bagi beberapa pihak, terkhusus anak muda yang menyandang status generasi Z (generasi yang lahir di tahun 1995 – 2010) dalam menjaga kesehatan mentalnya saat dihadapkan masalah. Banyak musabab dari fenomena ini. Tumbuh dan berkembang diiringi dengan kemajuan teknologi membuat generasi Z dapat terhubung dengan mudah untuk mengakses informasi kesehatan mental.
Menjadi kabar baik saat nyatanya generasi Z menyadari dan peka akan pentingnya bantuan profesional dalam menghadapi masalah kesehatan mental.

Salah seorang Psikolog Anak dan Remaja di Sumatera Utara, Eka Ervika menekankan bahwa kesadaran generasi Z terhadap pentingnya layanan kesehatan mental semakin meningkat, ditandai adanya peningkatan kunjungan mereka ke psikolog. “Kesadaran gen Z untuk menggunakan layanan psikolog sudah semakin tinggi, Menurut saya ini hal yang positif karena mereka tahu harus menggunakan bantuan professional,” terangnya.
Pernyataan ini sejalan dengan laporan American Psychiatric Association yang menunjukkan bahwa generasi Z lebih cenderung menerima pengobatan atau menjalani terapi (37%) disusul dengan generasi Millenial (35%), dan Gen X’ers (26%). Senada dengan laporan American Psychological Association, yang memaparkan bahwa Generasi Z secara signifikan melaporkan kesehatan mental mereka secara berkala. Lebih lanjut, nyatanya, lebih dari sembilan dari 10 orang dewasa gen Z (91%) mengatakan mereka pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional karena stres.
Era globalisasi telah membawa perubahan dalam banyak aspek. Keterbukaan akses pada teknologi dan internet turut berkontribusi dalam penyebarluasan awareness pada gangguan dan kesehatan mental.
Adalah paradoks ketika kesehatan dan isu mental terlalu diagung-agungkan dan diromantisasi secara ‘berlebihan’ bagi beberapa generasi yang sama. Modernisasi dalam pengaksesan informasi seperti ini berpotensi menjadi bumerang bagi generasi Z dan berdampak pada kerentanan terhadap kesehatan mental, seperti adanya rasa tidak aman (insecurity) saat berselancar di lini masa media sosial, fenomena self-diagnose, depresi, hingga copycat suicide nyatanya masih menggerayangi saat ini. Hal ini juga turut memunculkan stigma buruk pada generasi Z yang sering digadang-gadang dengan predikat “lebay” dan menjadikan kesehatan mental sebagai tameng untuk mewajarkan segala tindakan.
Kecenderungan Romantisasi dan Menjadi “Dokter” bagi Diri Sendiri

Romantisasi gangguan jiwa. Begitulah sebutan yang tepat untuk menggambarkan kutipan di atas. Mewakilkan kondisi individu, terutama gen Z yang cenderung menganggap menarik saat didiagnosis depresi atau gangguan mental lainnya.
Eka menjelaskan bahwa individu dengan kondisi ini mungkin merasa bahwa gangguan mental merupakan alasan bagi mayoritas perilaku mereka. Menciptakan semacam permakluman dari orang lain terhadap perilaku mereka, dengan mengkambinghitamkan gangguan mental.
Berkaca dari hal ini, salah satu mahasiswa berstatus generasi Z, Ghufran al Raafi mengaku bahwa tak sedikit teman sebaya yang dikenalnya melakukan beberapa tindakan, seperti mengunggah jenis gangguan mental dan menjelaskan bahwa mereka adalah penyintas gangguan tersebut, hingga tindakan ekstrem seperti menyayat tangannya sendiri, lalu diunggah ke media sosial.
Raafi berpendapat bahwasanya individu seperti ini terkadang hanya membutuhkan perhatian dan perlu didengar. “Pertama saya kasih ruang untuk bercerita, agar dia tau kalo masih ada yang peduli. Jika hadirnya saya tidak cukup membantu, maka saya sarankan dia ke profesional seperti psikolog atau psikiater,” jelasnya.
Sejalan dengan Raafi, berangkat dari kejadian tersebut, Eka menyarankan untuk menggunakan tahapan dalam menangani isu-isu kesehatan mental. Nyatanya, tak semua isu kesehatan mental memerlukan bantuan psikolog. Ada beberapa opsi untuk mengatasi masalah kesehatan mental dengan mencari dukungan dari beberapa pihak, seperti keluarga, guru, atau teman-teman terlebih dahulu. “Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi di lingkungan terdekat, maka penting untuk mempertimbangkan bantuan profesional,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk merawat kesehatan mental, dan yang terbaik akan bergantung pada kebutuhan individu.
Menumbuk di periuk, bertanak di lesung. Sudilah peribahasa ini kita tanamkan bersama. Sejatinya, dibutuhkan pendidikan yang bertahun-tahun bagi seseorang dalam memperoleh hak untuk menegakkan diagnosa atas suatu gangguan atau penyakit. Meraup informasi setengah-setengah pada akhirnya membuat gen Z membudayakan tindakan menegakkan diagnosa layaknya dokter atas diri sendiri. Tindakan ini dikenal dengan sebutan self-diagnose. Self diagnose merupakan keadaan seseorang yang berasumsi tentang masalah kesehatan yang dialami dan mendiagnosis diri sebagai pengidap gangguan mental tanpa bantuan profesional (Kaligis, 2021).
Self diagnose akan kesehatan mental terjadi karena kurangnya pemahaman generasi muda. Alih-alih ke pihak profesional, mereka cenderung mengandalkan informasi dari internet untuk menetapkan diagnosa sendiri dan meyakini sebagai sebuah kebenaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annury, dkk. (2021) terdapat 24,80% total dari 100 remaja generasi Z SMA di seluruh Indonesia melakukan self diagnose. “Dalam konsultasi, sering kali saya harus meluruskan bahwa tidak semua gejala yang dirasakan oleh mereka merupakan indikasi gangguan mental yang sebenarnya mereka alami. Jadi tidak boleh berlebihan,” ujar Eka.
Membaca pengetahuan pun butuh pengetahuan. Bak pisau bermata dua, teknologi yang bermanfaat nyatanya bisa menjadi bumerang atas penyalahgunaannya. Sudah seharusnya mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Menegakkan diagnosa tak semudah membaca ciri atau tips dari internet.
Penyebab Gen Z Rentan Alami Depresi
Antrian panjang memenuhi Poliklinik USU, baik petugas administrasi dan tenaga kesehatan rasanya cukup kewalahan di hari itu. Mulai dari poli umum, poli gigi, hingga poli spesialis, seperti poli mata, dan poli Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) secara bergilir menyambut wajah-wajah pasien yang berasal dari kalangan mahasiswa. Nampaknya penyakit sedang berkenan hinggap di tubuh beberapa mahasiswa yang datang untuk berobat.
Namun, terdapat sebuah ruangan paling tak bergeming. Barangkali ruangan ini yang menduduki hirarki teratas sebagai ruangan paling privat di antara yang lain; terbalut dengan dinding serta jendela berbahan kaca tebal buram, membuat aktivitas dalam ruangan tidak dapat dijangkau dari luar.

Ruangan itu bernama Poli Psikologi, kurang lebih satu tahun telah melayani konseling bagi mahasiswa USU. Tiap minggunya, mampu melayani sekitar 10 mahasiswa yang cukup berani untuk menyerahkan pergumulannya kepada psikolog.
Kedua psikolog yang melayani di sana, Debby Anggraini Daulay dan Sri Supriyantini menjelaskan bahwa di antara kasus yang ada, yang paling banyak, datang dari kasus stres dan depresi mahasiswa. “Sekitar 70 persen dalam satu tahun terakhir didapatkan kasus depresi mahasiswa,” terang Yanti.
Gangguan mental seperti depresi saat ini umum dialami oleh generasi Z. Menurut Eka, faktor yang paling berpengaruh yaitu kurangnya pengalaman menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara terdapat beberapa rintangan lain yang menyertai, seperti perundungan (bullying), terlilit hutang, menganggur, dan gejolak keluarga turut menghiasi daftar penyebab kerentanan depresi.
Ditambah lagi, dilansir dari laporan verywellmind, generasi muda nyatanya harus menghadapi ketidakpastian pasar kerja dan masa depan finansial. Mereka juga memiliki kekayaan yang jauh lebih sedikit daripada generasi sebelumnya saat memasuki usia yang sama. Adanya tekanan ekonomi yang berkelanjutan terus mengorbankan kaum muda sebagai korban finansial, seperti kesusahan mencari lowongan pekerjaan dan adanya Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).
Belum lagi pemberitaan negatif yang menghiasi lini masa media sosial, adanya rasa takut ketertinggalan segala sesuatu terbaru yang mempengaruhi kepercayaan diri, yang dikenal sebagai istilah Fear of Missing Out (FOMO), serta adanya perasaan malu karena gagal memenuhi standar sukses dan sempurna dalam norma masyarakat dan media massa.
Yang tampak kadang tak sesuai letak, yang di permukaan tidak bisa mewakilkan kedalaman. Bagai buah stroberi; merah merona dengan postur eksotis nyatanya mudah sekali hancur. Perumpamaan ini juga menjadi perbincangan hangat belakangan ini: Generasi Stroberi. Professor Rhenald Kasali (2017) merepresentasikan generasi Z seperti buah stroberi. Generasi yang kreatif dengan ide yang silih berganti, tetapi mudah dihancurkan oleh tekanan (Kasali, 2017).
Rasanya sudah cukup sering kita dikejutkan dengan pemberitaan bunuh diri datang dari mayoritas anak muda. Argumen di atas dapat diperkuat dengan data WHO pada Agustus 2023, faktanya terdapat lebih dari 700 ribu orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya dan menjadi penyebab kematian terbesar keempat pada kelompok usia 15-29 tahun. Cukup meresahkan. Mengingat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemimpin bangsa merupakan anak-anak muda dengan generasi Z di dalamnya.
Mengacu pada data dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) pada Oktober 2023, data di Indonesia menunjukkan sebanyak 6.1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Dalam tulisan yang sama, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Khamelia Malik menyatakan bahwa secara fisik, generasi ini memiliki periode paling sehat secara fisik, baik kapasitas tubuh maupun kecepatan dalam berpikir dan penalaran. Namun, adanya ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan perilaku yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian mencapai hingga 200%.
Fakta ini nampaknya mendukung hipotesis bahwa generasi Z adalah generasi yang tidak cukup tangguh dalam menghadapi tekanan dan mudah digerus emosi negatif. Padahal, secara kasat mata, nampaknya generasi muda memiliki lebih sedikit alasan untuk merasa stres dibandingkan generasi lainnya; belum memiliki keluarga yang harus dinafkahi, mayoritas generasi Z masih difasilitasi orang tua, tumbuh dengan ponsel pintar, dan akses teknologi canggih yang memudahkan.
Di sisi lain, faktor terbesar timbulnya generasi stroberi adalah pola asuh orang tua. Orang tua masa kini pada umumnya mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera dan membuat mereka memanjakan anak dan berdampak pada kelemahan anak, baik secara fisik maupun mental (Hapsari, Meilani, & Nabila, 2021).
Sementara menurut Eka, adanya kemajuan teknologi yang membuat Generasi Z diberi kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan mereka juga turut berkontribusi dalam menciptakan karakteristik ‘stroberi’. Segala sesuatu, mulai dari belanja hingga hiburan, belajar, dan bahkan sosialisasi, dapat diakses dengan mudah melalui perangkat genggam. Meskipun ini mempermudah hidup, namun kurangnya tantangan dapat membuat Generasi Z kurang terbiasa menghadapi kesulitan. “Membiasakan kesulitan bagi generasi Z untuk belajar mengatasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan,” tutur Eka.
Sumbangsih Negara untuk Kesehatan Mental Anak Muda
Eka turut senang dan bersyukur atas keberlimpahan tenaga kesehatan mental, terutama para psikolog dan psikiater yang semakin melimpah dibandingkan beberapa tahun ke belakang. “Mulai menjamurnya mahasiswa psikologi di banyak universitas menandakan banyak peminat yang ingin menjelajahi ranah batin manusia, sehingga jumlah para ahli psikis meningkat tajam,” pungkasnya.
Tak hanya berkiprah dalam lingkup rumah sakit atau klinik, tapi juga merambah ke layanan primer, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bahkan membuka praktek pribadi serta jasa konsultasi daring melalui layanan aplikasi.
Tersedianya fasilitas konsultasi online turut memecahkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh sebagian individu dalam mengakses bantuan psikologis, entah itu karena malu atau jarak geografis yang memisahkan. Ragam fasilitas, baik yang berbayar maupun gratis, kini telah menghampiri, termasuk di dalam lingkup rumah sakit dengan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menjadikan akses terhadap kesehatan mental semakin terbuka lebar.
Dilansir dari kompas.tv, konsultasi ke psikolog atau psikiater kini dapat menggunakan BPJS Kesehatan dan biasanya dapat dijumpai di rumah sakit atau puskesmas sehingga biaya perawatan kesehatan di keduanya masih menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Terdapat 4 cara dalam menggunakan layanan psikolog melalui BPJS Kesehatan. Pertama, dapat langsung mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau faskes pertama. Kedua, mengurus bagian administrasi. Ketiga, konsultasi, serta yang keempat yakni mengambil rujukan obat.
Namun demikian, kesadaran dan keputusan individu untuk mengambil langkah dalam pemanfaatannya tetap menjadi poin krusial, mengingat panjangnya regulasi yang mesti dipenuhi, demikian juga dalam memilih layanan yang tepat dan berkualitas.
Peran Kampus dalam Mendongkrak Kesehatan Mental Gen Z

Sejalan dengan Eka, Debby mengaku senang bahwasanya secara sadar, generasi Z khususnya mahasiswa USU masih peka tentang kebutuhan mereka dengan mendatangi layanan konseling gratis di Poliklinik. Seraya mengernyitkan dahi, Debby menjelaskan berbagai macam mahasiswa yang hadir untuk berkonseling–mulai dari murungnya muka hingga tubuh penuh luka. “Faktor yang disebabkan juga banyak, seperti keluarga, masalah perkuliahan, ekonomi, percintaan, dan lain-lain,” paparnya.
Kendati demikian, menurut pengakuan Debby, terdapat beberapa kasus dari mahasiswa yang membatalkan secara tiba-tiba jadwal sesi konseling yang telah disepakati. Hal ini segambar dengan beberapa pengakuan dari sejumlah mahasiswa kepada Wacana yang masih maju-mundur untuk menyerahkan permasalahan psikologisnya kepada poli psikologi di poliklinik. Beberapa penuturan dari mereka merasa ragu akan terjaminnya keamanan data dan faktor sosial.
“Takut nanti saat saya keluar dari ruangan konseling, ketemu teman di Poliklinik terus dia tau,” ungkap salah seorang mahasiswa USU yang tak ingin disebut namanya.
Menanggapi hal ini, Debby meluruskan bahwasanya sebagai psikolog, adalah hal penting untuk menutup rapat data asesmen konseling sebagai salah satu kode etik seorang psikolog. “Selain itu, ruangan konseling dibuat lebih tertutup dan pintu keluar diarahkan dari samping poliklinik guna untuk menjaga privasi mahasiswa,” pungkasnya.

Selain itu, perlu diketahui bahwa selain fasilitas konseling gratis di Poliklinik, Fakultas Psikologi USU memiliki layanan psikologis tak hanya bagi mahasiswa tapi juga untuk masyarakat, yang dikenal sebagai Pusat Pelayanan Psikologi pada Masyarakat (P3M). Lebih dari sekadar konseling, P3M menawarkan jasa psikologis, seperti pemeriksaan psikologi, psikotes dan tes minat bakat, psikoterapi, dan lain-lain.
Dalam memfasilitasi kesehatan mental, dapat dikatakan USU menyediakan banyak ruang bagi mahasiswanya. Ditambah lagi, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini USU akan menambahkan tes kesehatan mental bagi mahasiswa baru angkatan 2024. Baik Yanti maupun Debby mengonfirmasi hal ini guna untuk melihat kesiapan mahasiswa secara mental.
Rasanya dalam hal ini, USU patut dijadikan teladan bagi kampus-kampus lain dalam memfasilitasi kebutuhan akan kesejahteraan mental mahasiswanya.
Peran Media dalam Pemberitaan Kasus Kesehatan Mental
Hidup melekat dengan teknologi pasti tak lepas dengan paparan media. Cara media menyiarkan pemberitaan soal kasus bunuh diri rasanya patut menjadi sorotan khusus, terutama dengan adanya upaya global dalam pencegahan epidemi bunuh diri, yang dikenal sebagai werther effect.
Lagi-lagi teknologi. Eka mengatakan bahwa penggunaan teknologi telah mempercepat dan memperluas penyebaran informasi, yang memiliki dampak yang lebih serius terhadap generasi Z. Generasi Z yang masih dalam tahap transisi antara anak-anak dan dewasa, rentan terhadap tren negatif seperti menyakiti diri sendiri (self-harm). “Tren menunjukkan perilaku berbahaya dengan cepat menjadi viral dan ditiru oleh individu yang rentan, terutama jika mereka merasa terisolasi atau tertekan,”ujarnya.
Kehadiran teknologi memerlukan peran penting orang tua, guru, dan masyarakat. Mereka harus menjadi pemandu yang bijak bagi generasi Z dalam menyikapi informasi dan merangkai pemahaman tentang segala dampaknya. Keluarga yang hangat dan sejahtera memegang peranan utama, melindungi mereka dari arus negatif teknologi, dan membawa cahaya pertumbuhan yang positif.
Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab moral, harus menjadi penyampai yang cerdas, memahami impaknya pada pendengar, terutama generasi Z. Pendidikan literasi media menjadi landasan penting, agar mereka mampu menyaring informasi dengan mata yang cerdas, dan memahami konsekuensi setiap tindakan.
Bagaimana seharusnya Generasi Z?
Banyak jalan menuju Roma. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memelihara kesehatan mental dan mencegah terjadinya gangguan. Seni merawat diri ini dikenal dengan sebutan coping stress. Berdasarkan Journal of Personality and Social Psychology, Coping stress merupakan upaya kognitif dan perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan/atau tuntutan internal tertentu yang dianggap melebihi sumber daya yang ada pada individu tersebut.
Terdapat dua cara untuk melakukan coping stres, yaitu emotion focused coping dan problem focused coping.
Emotion focused coping berfokus menangani stres secara internal melalui respon emosional individu terhadap kondisi dan situasi yang sedang dialami, khususnya dengan pertahanan psikologis dari ketidakberdayaan. Fokusnya untuk mengurangi stres dengan menenangkan diri. Sementara Problem focused coping merupakan penanganan stres dengan cara mencari sumber masalah, menghadapi masalah dan menyelesaikannya.
Pengontrolan diri adalah saat kita memilih opsi emotion focused coping, berfokus pada usaha yang disadari guna menurunkan emosi negatif yang dirasakan ketika menghadapi masalah atau tekanan.
Pun emotion focused coping efektif dalam mengelola emosi dan reaksi psikologis, tetapi tidak dapat mengatasi akar penyebab dari stres. Setelah merasa lebih tenang, individu dapat beralih ke problem focused coping untuk menemukan solusi yang lebih langsung terhadap penyebab stres.
Namun tetap saja, Eka menekankan bahwasanya tak hanya anak muda yang patut diperhatikan. Keselarasan sehat mental dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang turut berkontribusi pada kehidupan sosial generasi Z juga patut menjadi sorotan. “Karena apabila dalam suatu lingkungan ada yang tidak sehat mental, itu akan mempengaruhi kesehatan mental yang lain. Jadi tugas kita menjaga sama-sama agar tetap sehat dan membuat semuanya jadi sehat,” tegasnya.
Pada akhirnya, dalam rangka menumbuhkan kesehatan mental di setiap individu, terkhusus generasi Z yang akan mewarisi masa depan bangsa, dibutuhkan campur tangan dari berbagai pihak, tak terkecuali upaya generasi Z dan lingkungan sekitarnya. Semoga dari segala kesusahan hidup yang boleh kita rasakan, kita masih memiliki cukup ruang untuk saling mengerti dan peduli.
***
Koordinator Liputan: Rachel Caroline L.Toruan
Reporter: Mila Audia Putri


