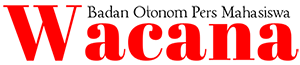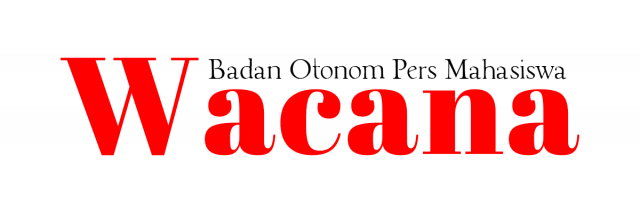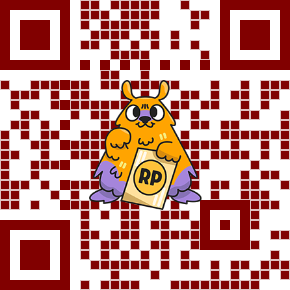Oleh : Muhammad Sidratul Muntaha Idham
| Judul | Dongeng Pulau Tak Dikenal |
| Penulis | Jose Saramago |
| Penerjemah | Ronny Agustinus |
| Penerbit | Circa |
| Tebal | 50 Halaman |
I
Seorang lelaki, yang badannya dikudungi selimut, rebahan di depan pintu petisi kerajaan. Ia adalah seorang dari sekian ratus ribu orang yang mengadu persoalan di hadapan kediaman raja. Tapi si Raja pura-pura tuli. Biar menteri pertama, kedua dan seterusnya, sederetan tetek-bengek birokrasi, hingga babu wanita yang mengurus persoalan rakyat jelata.
Lelaki itu kehilangan dirinya. Ia meminta kapal pada Raja untuk mencari dirinya yang hilang di pulau tak dikenal. Ia tak akan menyingkir dari pintu sebelum Raja sendiri yang mendatangi dan memenuhi permintaanya.
Beri dia kapal, beri dia kapal, kata sebagian rakyat yang mungkin merasa senasib sepenanggungan. Sebagian lain meminta hal yang sama agar lelaki itu pergi dari hadapan pintu petisi dan memberi giliran pada orang lain meminta pada Raja. Omong kosong tak ada pulau tak dikenal, kata Raja. Pejabat lain bisu. Babu Wanita memanggil hulubalang untuk memulihkan ketertiban.
Lelaki itu mungkin tak peduli dengan segala ungkapan dan kebisuan yang meluncur dan merayap di sekelilingnya. Sebab, ia kini hanya ingin mencari dirinya yang lenyap entah kemana. Setelah berkeras otot leher dengan Raja dan masyarakat lain yang ikut-ikutan, Raja memberinya kartu yang mencantumkan kata-kata berikut namanya untuk dikirim ke syahbandar, agar lelaki itu diberi kapal.
Lelaki itu kemudian mendatangi syahbandar, di sebuah dermaga, untuk meminta kapal yang akan mengantarnya ke pulau tak dikenal. Tapi apa itu pulau tak dikenal? Apa pulau yang dikenal? Apakah pulau yang dikenal adalah titik-titik di atas peta? Yang manusia beri nama?
Semua orang bisa heran dan terperanjat seperti Raja ketika kali pertama mendengar permintaan lelaki itu: pulau tak dikenal apa ini yang kau cari? Namun benar kata lelaki itu, andai saya bisa mengatakannya pada anda, maka pulau itu sudah dikenal.
Syahbandar juga heran akan keinginan lelaki itu. Bersitegang pula mereka berdua. Hingga akhirnya si Lelaki diberi kapal kerakah, aman dan laik melaut. Babu Wanita ternyata membuntuti lelaki itu dan ingin menjadi awak kapal pertama dan satu-satunya: sebagai tukang bersih-bersih kapal.
Mereka berdua menaiki kapal, disambut burung-burung camar yang berhamburan dan berkaok-kaok buas. Tiada jatah makanan dalam lemari makanan dan layar kapal kusut karena tak pernah dipakai. Mereka juga tak punya pengalaman melaut. Si Lelaki tak punya profesi dan keterampilan. Ia punya, pernah punya, dan akan punya pernah bila perlu, tapi ia ingin mencari Pulau Tak Dikenal, kata lelaki itu.
Ia mengimbuhkan “aku ingin mencari tahu siapa aku ketika tiba di pulau itu. Tidakkah kau sudah tahu, Bila kau tidak melangkah keluar dari dirimu sendiri, kau takkan pernah menemukan siapa dirimu.”
II
Manusia punya kebutuhan untuk percaya. Orang-orang abad pertengahan butuh percaya pada pemegang wahyu Tuhan. Manusia modern butuh percaya pada otoritas pengetahuan. Dari situlah derajat kelemahan dan kekuatan manusia ditilik Nietzsche.
Kebutuhan untuk percaya melahirkan pemikiran Nietzsche tentang idee fixe, ide yang fiksatif, yang diidentifikasi secara fixed, yang dipejalkan dan dimampatkan sebagai hal final. Ilahiah.
Nietzsche mengkritik idee fixe dalam rupa apapun. Filsuf juga tak luput dari kritiknya, disebutnya sebagai pemuja mumi. Sebab, ia menciptakan konsep di semesta peristilahan dan memberinya materai agar kekal dan diingat sejarah.
Maka baik si Raja maupun syahbandar sedikit-banyak juga mirip pemuja mumi. Mereka semua tak acuh dengan pulau tak dikenal sebab ia tak ada di peta. Mereka hanya memercayai petunjuk arah, yang mencatat pulau-pulau pada titik-titik kordinat, yang mereka anggap fiksatif dan final.
Sementara lelaki pencari pulau tak dikenal, yang tak ia ketahui letak dan titik kordinatnya, hanyalah orang yang kepalanya diliputi waham dan pantas ditertawakan di dunia yang sok waras.
Namun tak ada yang tersisa dari dirinya untuk diperolok. Filsuf eksistensialis mungkin akan memuji lelaki itu. Ia akan dipuji atas keberaniannya mencari diri sendiri di pulau tak dikenal. Orang-orang yang memperjuangkan eksistensinya sedemikian rupa, layak untuk itu.
Sartre akan memuji lelaki itu karena ia tak serta-merta menerima esensi yang disematkan atas dirinya. Ia bukan sekadar pelayan kafe yang ramah karena diberi mandat oleh bos, diberi tip oleh pelanggan. Ia tak ingin esensi mendahului eksistensinya.
Camus tak akan mengatainya pecundang. Pencarian atas makna memang kesia-siaan. “Pencarian sia-sia itu,” kata Camus. Seperti Sisifus yang dikutuk selama-lamanya mendorong batu karang ke puncak gunung, yang pada akhirnya akan selalu bergulir kembali ke lereng. “Tapi perjuangan itu sudah cukup mengisi hati manusia.” Pun demikian perjuangan lelaki yang mencari diri sendiri di pulau tak dikenal, entah ia akan menemukannya atau tidak.
Kembali pada Nietzsche. Setyo Wibowo dalam bukunya Gaya Filsafat Nietzsche menyebut Nietzsche sebagai seniman yang tak berhenti mencari. Ia mendobrak segala kemapanan, kepuasan diri, dan forma apapun.
Hidup Nietzsche berakhir bersama sifilis dan kegilaan yang bersarang dalam tubuh dan kepalanya. Sebagai orang sinting, ia kini menjadi salah satu filsuf paling seksi dan sering dikutip. Lalu bagaimana nasib lelaki, yang tak kurang gila, ciptaan Jose Saramago dalam novelanya Dongeng Pulau Tak Dikenal ini?
III
Saya setengah terbaring di indekos sendirian, menghabiskan novela tipis Saramago sekali duduk, waktu yang sangat singkat untuk durasi imbauan social distancing di tengah pandemi. Kendati demikian, novela ini tak kurang rumit untuk dilahap. Percakapan, dialog dan kalimat langsung dari setiap tokoh tak diberi tanda kutip. Tanpa tanda kutip, bentuk kalimat-kalimat dalam paragrafnya menjadi tak lazim.
Saya kutip salah satu kalimat dari bagian novela tersebut: “Wanita itu mengulurkan lilin padanya, berkata, Sampai jumpa besok, lalu, tidurlah yang nyenyak, lelaki itu ingin mengucapkan hal yang sama, hanya saja secara berbeda, Mimpi yang indah, itulah frase yang ia cetuskan, sebentar sesudahnya, ketika berada di bawah, berbaring di depannya, kalimat-kalimat lain lantas terlintas di benaknya, kalimat-kalimat yang lebih cerdas, lebih memikat, sebagaimana seharusnya yang diucapkan seorang lelaki ketika ia mendapati dirinya berduaan bersama seorang wanita (hlm. 41).”
Kalimat di atas adalah reka adegan si Lelaki dan Babu Wanita yang bersiap-siap tidur setelah menjelajahi seisi kapal. Jika ungkapan langsung si Lelaki dan Babu Wanita tak ditandai dengan huruf kapital, tentu sulit bagi pembaca membedakan ungkapan narator dan kedua tokoh tersebut.
Namun persis di sini pula, Saramago membuat penggunaan huruf kapital menjadi tak lazim. Huruf kapital yang seharusnya menjadi pembuka kalimat, bisa muncul di mana saja: awal, tengah atau akhir kalimat.
Saramago membongkar kelaziman tanda baca dan aturan huruf-huruf. Ejaan bahasanya yang tak umum membuat pencarian kita atas makna di tiap paragraf menjadi lebih intens.
Tak ada yang perlu didewakan dari tanda baca, ejaan bahasa, dan struktur kalimat berupa subjek dan predikat dan objek dan keterangan dengan seluruh jenisnya yang membikin segala hal terlalu jelas. Tanda baca dan ejaan yang dibuat seenaknya oleh Saramago, bagi saya, adalah bentuk ketidakpercayaannya pada titik kordinat dalam petunjuk arah.
Kalimat paling kasar dan agitatif sekalipun akan menjadi ringkih jika terlalu tunduk pada ejaan dan tanda baca. Sementara orang-orang purposif, jiwa yang gelisah, butuh akan pencarian yang anarkis. Ejaan yang tak lazim melengkapi pencarian si Lelaki memburu dirinya di pulau tak dikenal.
Saya membaca nyaring kalimat demi kalimat Dongeng Pulau Tak Dikenal untuk menjaga fokus. Suara saya mengiringi si Lelaki dan Babu Wanita yang berbaring di depan masing-masing di ujung cerita. Belum membentangkan layar. Lelaki itu lantas bermimpi layarnya terkembang dan awak kapal tiba-tiba memenuhi geladak bersama bebek, kelinci, ayam, ternak piaraan lazimnya.
Awak kapal memutuskan memanfaatkan perjalanan lelaki itu. Mereka mengacau pengarungan lelaki itu dan mencari pulau yang ada di peta.
Mereka mengubah haluan menuju pulau yang dikenal, memasuki pelabuhan, merapat ke gelangan. Awak kapal pergi dan membawa serta hewan piaraan. Tapi mereka tidak membawa pohon-pohon, gandum dan bunga-bunga, begitu pula tanaman merambat yang melingkari sekeliling layar dan menghiasi lunas-lunas kapal.
Dan kapal itu kini menjadi Pulau Tak Dikenal. “Hampir tengah hari, bersama arus, Pulau Tak Dikenal akhirnya melarung ke samudra, mencari dirinya sendiri.” (hlm. 50).
IV
Lelaki itu adalah Pulau Tak Dikenal adalah diri tak utuh yang mencari adalah Saramago yang memberontak bentuk.
Muhammad Sidratul Muntaha Idham. Akrab disapa Sidra, Redaktur Lembaga Pers Mahasiswa Arena.