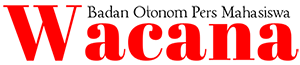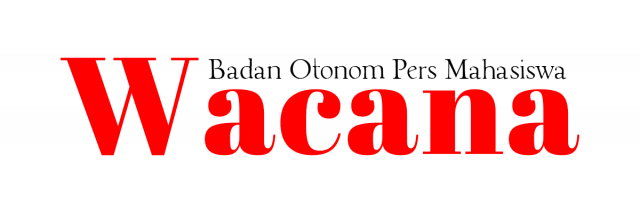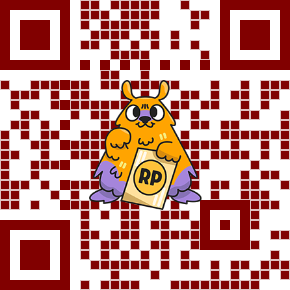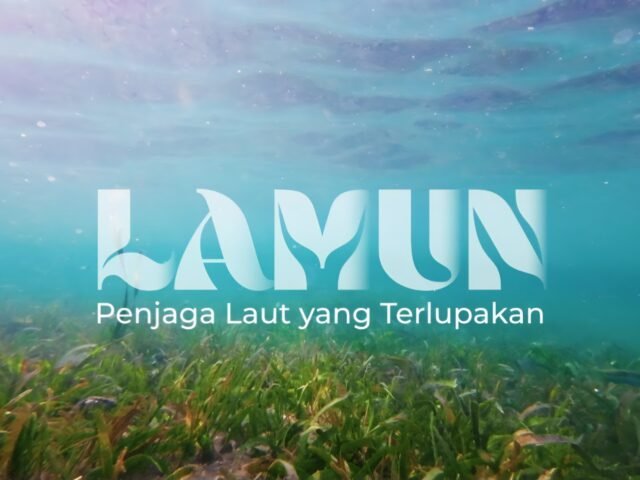
Oleh: Firda Elisa
|
Judul |
Lamun: Penjaga Laut yang Terlupakan |
|
Produser |
Olivia Laurent |
|
Direktur |
Olivia Laurent |
|
Rilis |
2 Juni 2025 |
|
Durasi |
35 menit 38 detik |
|
Genre |
Dokumenter |
|
Tersedia di |
Dengan kesederhanaannya, ia berperan menjaga ekosistem pesisir dan melindungi kehidupan di laut maupun di darat.
Namanya “Lamun”, salah satu jenis tumbuhan yang hidup di bawah laut, tepatnya di daerah pesisir. Penjaga pesisir satu ini tidak berwarna-warni seperti terumbu karang, tidak pula tinggi menjulang seperti mangrove.
Dalam film, ditunjukkan lamun memiliki peran yang sama pentingnya dengan mangrove dan terumbu karang. Namun, tumbuhan ini kurang mendapat sorotan masyarakat sekitar karena sering dianggap sebagai rumput liar yang mengganggu pemandangan.
Kehidupan ketiga spesies penjaga daerah pesisir ini, dapat ditemui di Pulau Pramuka, salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Film ini menyoroti keberadaan padang lamun dan upaya konservasinya yang masih sangat minim mendapat perhatian.
Pulau Pramuka menjadi tempat Taman Nasional Kepulauan Seribu berdiri. Sekaligus menjadi tempat tinggal bagi komunitas pesisir yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut dan ekowisata. Pulau ini menjadi habitat untuk setidaknya tujuh spesies lamun. Empat dari spesies yang paling sering ditemukan antara lain; Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata dan Halodule uninervis.
Bagi para nelayan dan masyarakat lokal, lamun menjadi penopang hidup mereka. Lamun turut mendukung populasi ikan, bintang laut, dan kerang-kerang yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak hanya itu, lamun juga menjadi sumber makanan bagi spesies langka seperti penyu dan dugong.

Dalam film ini juga dipaparkan tiga fungsi utama lamun. Pertama, fungsi ekologi, yakni sebagai sistem penyaring alami yang menyaring kotoran, debu, dan partikel air. Jaringan akarnya yang kompleks dapat meningkatkan kejernihan dan kualitas air laut. Alasan inilah yang buat daun lamun terlihat kotor.
Secara fungsi biologi, lamun dapat menyediakan nutrien bagi hewan laut dan terumbu karang. Kemudian fungsi ekonomi, lamun berperan sebagai tempat tinggal bagi ikan-ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat.
Faktanya, padang lamun merupakan salah satu ekosistem paling produktif di bumi. Lebih dari 20 persen usaha perikanan di dunia bergantung pada keberadaan hamparan lamun dalam perekonomian.
Dalam hal melawan perubahan iklim, lamun mampu menyerap karbon dioksida 35 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis. Dengan alasan tersebut, lamun dapat menjadi solusi alami yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim.
Ancaman utama bagi lamun
Secara global, padang lamun mengalami penurunan hingga 7 persen tiap tahunnya. Sejak tahun 1980-an, Indonesia telah kehilangan sekitar 30–40 persen dari total hamparan lamun, demikian pula keadaan di Pulau Pramuka. Faktornya disebabkan karena pembangunan infrastruktur pesisir, polusi, dan aktivitas manusia.
Salah satu narasumber yang ditampilkan dalam film ini, Prof. Pramaditya Wicaksono, Koordinator The Indonesian, Seagrass Mopping Partnership, menjelaskan bahwa ancaman terbesar lamun adalah literasi.
“Karena kalau kita nggak paham apa yang mau kita kelola, otomatis kan, pengelolaan kurang optimal. Nah, dampak dari kurangnya literasi terkait padang lamun ini otomatis akan muncul ancaman. Ancaman yang sering terjadi di Indonesia utamanya adalah reklamasi pantai, kompetisi ruang dengan budidaya aquaculture yang dilaksanakan di padang lamun, belum lagi limbah-limbah dari aktivitas manusia,” paparnya.
Salah seorang nelayan lokal, Ramli, juga mengakui bahwa banyaknya reklamasi menjadi penyebab hilangnya lamun. “Karena ditimbun sama batu buat urukan. Di samping itu, faktor alam juga mempengaruhi,” jelasnya.
Dampak dari hilangnya lamun ini dapat mengurangi pertahanan pulau terhadap erosi pantai. Serta, meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem.
Upaya konservasi lamun di Pulau Pramuka

Berdasarkan data dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, peningkatan tutupan lamun menunjukan perkembangan yang baik. Pada tahun 2018, sebesar 17 persen meningkat menjadi 33,84 persen pada tahun 2023.
Pulau Pramuka memiliki total empat stasiun konservasi yang dapat dimonitor, yakni stasiun Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Berbagai upaya konservasi lamun di pulau ini dijalankan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.
Salah satu metode pemulihan lamun yang dilakukan adalah transplantasi lamun di area yang mengalami kerusakan. Lamun yang sehat diambil dari lokasi yang stabil untuk kemudian dipindahkan ke area yang rusak atau terdegradasi.
Di dalam film ini, Agus Setiawan, Kepala Unit Polisi Hutan SPTN wilayah III Pulau Pramuka, memperlihatkan bagaimana transplantasi lamun dilakukan pada substrat yang berpasir. Metode yang dilakukan yaitu Transplanting Eelgrass Remotely with Frame System (TERFs) yang diadaptasi dari Australia.
Metode transplantasi ini dilakukan dengan bingkai untuk menempatkan dan mengamankan bibit lamun sebelum ditanam di dasar laut. Keberhasilan upaya konservasi ini tergantung pada metode yang digunakan dan pemantauan pasca-penanaman.
Dalam satu minggu pertama, pemantauan lamun menjadi hal yang krusial. Pada masa ini, area penanaman harus dibersihkan dari sampah, alga yang menempel, dan gangguan hewan pemakan daun. Untuk mendukung upaya konservasi, pemerintah bekerja sama dengan warga untuk memastikan tidak ada pembangunan di area padang lamun tanpa izin.
Film dokumenter ini dikemas dengan visual yang menarik dan narasi yang mudah dipahami. Tak lupa, sajian wawancara dengan warga lokal Pulau Pramuka, aktivis, hingga akademisi yang memberikan perspektif yang beragam tentang lamun.
Melalui film ini, membuat kita sadar bahwa setiap makhluk hidup di bumi memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sama halnya dengan lamun, apa yang terlihat sederhana, mungkin saja menjadi penopang bagi kehidupan makhluk hidup lain. Tidak hanya ikan-ikan kecil dan hewan laut, tetapi juga bagi manusia.