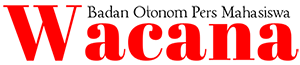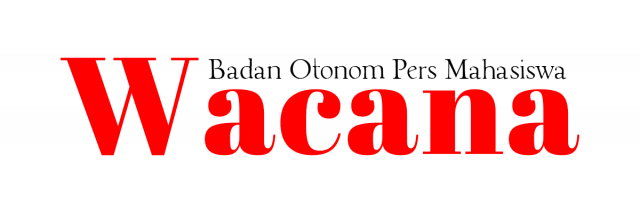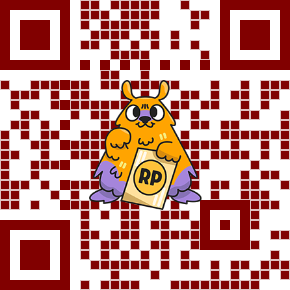Oleh: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis
Ketika proses hukum dan birokrasi justru menghadirkan ketidakpastian, banyak orang mulai menyebutnya dengan satu kata: Kafkaesque.
Hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari masalah, atau bahkan dikepung oleh sejumlah kesuraman yang tampak dari waktu ke waktu. Dengan kondisi demikian, kita frustrasi dalam menjalaninya, rasanya hidup membingungkan, dan tak masuk akal, seperti pada cerita fiksi. Perasaan tersebut bukan fiksi, melainkan fenomena Kafkaesque.
Kafkaesque sendiri merupakan ungkapan situasi dimana seseorang mengalami perasaan terasing, kesepian, dan putus asa atau bisa juga disebut surealis. Pengalaman surealis tersebut sungguh rumit dan menindas dan bagaikan mimpi buruk. Kafkaesque diambil dari nama belakang sastrawan Ceko yaitu, Franz Kafka.
Kafka dikenal dengan tulisannya yang bergaya absurditas. Lewat karya sastranya, Kafka menggambarkan situasi emosional dirinya. Perumpamaan-perumpamaan ia gunakan untuk menggambarkan kegelisahannya tentang eksistensi manusia yang teralienasi dari makna hidup. Orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menghadapi absurditas dan keanehan dari dunia.
Sifat dari manusia-manusia yang hidup di zaman postmodern, sering kali tampak terasa menyimpang. Mereka yang mengalami fenomena tidak biasa seperti ini, merasa terbelenggu akibat ancaman dan bahaya dalam dunia yang suram. Dalam ranah yang lebih luas, fenomena Kafkaesque sering kita jumpai dalam rumitnya birokrasi modern atau berbelitnya proses pengadilan.
Kafkasque di Indonesia Hari Ini
Kafka menjelaskan bagaimana manusia yang terjebak dalam birokrasi, alienasi, dan absurditas kehidupan sehari-hari sangat sulit dipahami. Misalnya saja dengan novelnya yang berjudul Metamorfosis, yang menceritakan seorang pria bernama Gregor Samsa. Gregor terbangun dari tidur dan mendapati dirinya berubah menjadi seekor serangga besar menjijikkan tanpa alasan yang jelas.
Alih-alih menolongnya, keluarganya menjauhi dan tidak berusaha memahami apa yang Gregor ingin utarakan. Mereka menganggap Gregor sebatas hama yang mengganggu dan harus disingkirkan. Hal ini selaras dengan kegelisahan publik beberapa waktu lalu terhadap revisi Undang-Undang TNI yang disahkan secara terburu-buru.
Masyarakat menilai bahwa UU TNI yang disahkan ini, justru hanya menimbulkan kesenjangan yang lebih kompleks antara rakyat dengan pemangku kekuasaan. Perubahan besar yang terjadi secara mendadak tanpa adanya ruang diskusi, menciptakan perasaan yang begitu Kafkaesque. Seperti halnya Gregor yang tidak paham apa yang terjadi pada tubuhnya, rakyat juga tidak memiliki akses penjelasan yang masuk akal dan merasa terasingkan.
Selain itu, dalam novel Kafka lainnya yang berjudul The Trial, sang tokoh utama Josef K. tiba-tiba ditangkap dan diadili tanpa alasan yang jelas. Josef tidak tahu otoritas mana yang bertanggung jawab atas kasusnya. Petugas yang menangkapnya hanya memberitahu bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Josef merasa mustahil ketika disuruh membela diri tanpa tahu apa tuduhannya.
Dalam novel ini, Kafka mencoba untuk mengulik tentang birokrasi sipil yang mengerikan. Ketika rakyat harus berhadapan dengan aturan yang tidak masuk akal dan sistem dengan substansi yang tidak jelas. Kisah Josef merefleksikan tema tentang alienasi, ketidakberdayaan, dan juga sifat aneh otoritas.
Warga negara bisa jadi alami Kafkasque
Karya-karya Kafka yang disebutkan sebelumnya menjadi cerminan sistem birokrasi yang tidak adil dan juga tidak bisa dipahami. Kafka menggambarkan absurditas yang cukup relevan dengan keadaan Indonesia sekarang. Banyak masyarakat malas ketika berurusan dengan layanan pemerintah yang berbelit-belit. Parahnya lagi, laporan akan diproses lebih lanjut jika diberi “uang rokok”. Bukannya mendapat perlindungan, korban yang dirugikan malah tersesat dalam sistem seperti yang dirasakan tokoh Josef, sungguh Kafkaesque.
Tak berhenti di situ, proses hukum juga menjerat orang-orang yang mencoba menyuarakan keadilan. Seperti yang terjadi pada vokalis band Sukatani. Ia mendapat intervensi dari pihak kepolisian, karena lirik dari lagu berjudul Bayar, bayar, bayar. Isi lagu tersebut menyuarakan kritik terhadap pihak terkait, berujung ia dipecat dari profesi aslinya yang merupakan seorang guru. Bukannya berbenah diri mereka malah menjerat kebebasan berekspresi lewat karya seni, sungguh Kafkaesque.
Novel Metamorfosis dan The Trial cukup relevan dengan keadaan negara kita sekarang ini. Fenomena Kafkaesque bukan sekadar istilah sastra, tapi lensa untuk memahami realitas. Ketika logika tak lagi bekerja, dan sistem tampak tak punya arah yang jelas. Mirip dengan kisah dalam karya Kafka yang absurd, melelahkan, dan penuh kesuraman. Jadi, sekarang fenomena Kafkasque itu bukanlah sekadar cerita fiksi.