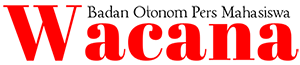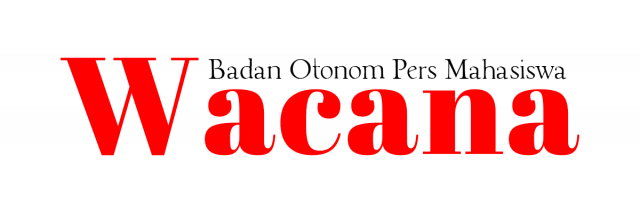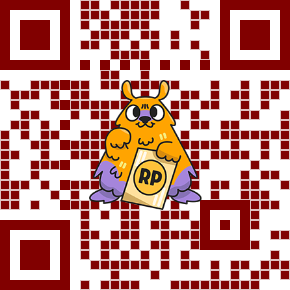Oleh: Dinar Fazira Fitri
“Ngapain imunisasi? Kalau sakit, tinggal bawa ke rumah sakit”
Terik matahari siang itu bisa menyengat kulit siapa saja yang tengah beraktivitas. Namun, hal tersebut sama sekali tak melunturkan semangat seorang kader Posyandu, Mastahulina Sianipar, yang sedang bertugas dalam pelaksanaan imunisasi di lingkungan rel kereta api, kawasan Medan Helvetia.
Setiap bulan, imunisasi rutin dilaksanakan pada hari Kamis di minggu kedua. Rumah Kepala lingkungan (Kepling) memang jadi Posyandu untuk warga setempat. Meja-meja pelayanan, timbangan, alat ukur sudah sedia sejak pukul 10.00 WIB. Satu demi satu, ibu dengan anaknya mulai padati bangku-bangku, menunggu nama sang anak dipanggil.
Pengadaan imunisasi tak hanya diumumkan lewat grup WhatsApp Posyandu. Mengingatkan dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, menjadi tugas kader tiap bulannya. Walau kadangkala sosialisasi itu, tak selalu disambut baik oleh orang tua si anak.
Mastahulina sering kali mendengar orang tua beralasan tak punya waktu bawa anaknya karena bekerja. “Ada orang tua yang lihat anaknya kondisi sehat, ngapain imunisasi? kalau sakit, kita bawa ke rumah sakit,” ujarnya menirukan perkataan salah satu ibu yang menolak anaknya diimunisasi, pada Kamis (10/7/2025).
“Tapi kalau orang tuanya bijak, pasti dia akan bawa anaknya imunisasi karena kan dampak imunisasi sampai ke dewasa,” tegasnya lagi.

Kesadaran itu belum tumbuh, dan rasa kemauan masih jauh. Kepala Lingkungan II di kawasan rel kereta api tersebut, Raden Hutagalung, berkata orang tua yang tak punya akses kendaraan, terkendala dalam membawa anaknya pergi imunisasi.
“Kadang sistem antar jemput juga. Ada yang anaknya dua, ada yang tiga. Karena dari ujung dia capek jalan dan nggak punya kendaraan, jadinya kita yang harus jemput bola,” ucapnya.
Mengenai penolakan, banyak pula orang tua yang menganggap imunisasi adalah barang berbahaya. “Masih banyak yang takut, kalau suntik Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT) yang efeknya akan demam,” ungkap Raden.
Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, sebanyak 54 Posyandu tersebar di Kecamatan Medan Helvetia. Di antaranya termasuk rumah-rumah Kepling di tepian rel yang dijadikan Posyandu.
“Kita sudah sediakan tempat dan segala macamnya. Sebenarnya, manusianya aja yang susah dibuka pola pikirnya. Mudah-mudahan terbuka lah hati warga ini,” harap Raden.
Kilas balik permukiman padat rel kereta api

Siang hari, suasana rel tak terlalu ramai, hanya terlihat satu-dua orang berjalan kaki menuju jalan raya. Sekitar 10 menit sekali, kereta api akan menunjukkan kehadirannya, yang buat lalu-lalang kendaraan terhenti sejenak. Dari jarak sembilan meter samping rel, tampak padat permukiman penduduk.
Sudah puluhan tahun, mereka hidup di sana. Di balik itu, ada kisah panjang yang melatarbelakanginya. Diceritakan oleh Dosen Ilmu Sejarah USU, Kiki Maulana Affandi. Ia menarik garis permukiman Medan yang dulunya dibentuk oleh Belanda kisaran tahun 1870-an.
Kota Medan pada mulanya dipimpin oleh dua pemerintahan. Satu pemerintahan kesultanan Deli, satu pemerintahan kolonialis Belanda. Di masa lampau, permukiman tersebut dibentuk oleh pemerintahan kolonial berdasarkan etnik. “Helvetia itu dulunya merupakan perkebunan, dia tidak termasuk kota,” sampainya.

Pada tahun 1957-1958, rel kereta api, kantor stasiun, semua aset tanah itu adalah milik perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij (sekarang menjadi PT. KAI). Setelah kemerdekaan, sistem perkebunan pun dinasionalisasi.
Tapi, perubahan besar baru terasa pada era 1970-1980an, ketika gelombang urbanisasi melanda Medan. Warga dari desa datang ke kota, dengan harapan mencari peruntungan hidup yang lebih baik. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, akhirnya banyak penduduk tinggal di pinggiran rel.
“Itu sudah jadi gejala pertumbuhan kota dengan pemukiman padat. Kota menawarkan pekerjaan, tapi tidak dengan tempat tinggal. Akhirnya orang-orang memilih tinggal di pinggiran rel,” ucap Kiki.

Rumah-rumah dibangun dengan bahan seadanya, berdiri di atas tanah yang sebenarnya milik PT. KAI, bekas konsesi perusahaan Deli Spoorweg Maatschappij di masa kolonial. Legalitasnya lemah, infrastruktur nyaris tak ada, tapi kehidupan terus berlangsung. Ada yang sudah tinggal di sana puluhan tahun, bahkan sampai beranak-cucu.
Lantas, apakah kawasan tersebut kini sudah mencapai standar permukiman layak? “Pastinya belum,” jawabnya tegas. “Dari zaman Belanda sampai sekarang, orang-orang yang tinggal di pinggiran rel tetaplah kelompok yang terpinggirkan.”
Pada tahun 2016–2017, pernah ada bantuan sanitasi untuk kawasan kumuh, tapi daerah permukiman rel tak banyak tersentuh. “Mungkin karena mereka tidak dianggap warga kota secara resmi. Padahal, mereka berhak atas akses dasar,” pungkas Kiki.
Akses imunisasi yang mereka butuhkan

Masih di kawasan Medan Helvetia, kondisi permukiman rel kereta api di jalan Pondok Kelapa tak jauh berbeda. Di depan rumahnya yang ditandai cat semprot oleh PT. KAI, Septi Wardani, menjelaskan bahwa rumah-rumah yang bertanda merah itu akan terkena perluasan jalur rel.
Penggusuran memang telah diwacanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan PT. KAI sejak lima tahun belakangan. Perihal itu, ia angkat bahu saja. Selagi anaknya bisa hidup sehat, ia tetap bersyukur. Itulah yang memupuk kemauannya untuk bawa anak imunisasi.
Sayangnya, tak semua warga berpikiran sama dengan ibu tiga orang anak itu. “Ada juga orang-orang sini yang nggak mau anaknya imunisasi, kadang karena malas. Takut anaknya kenapa-kenapa, karena pernah kejadian setelah imunisasi, ada yang sakitnya luar biasa sampai meninggal,” beber Septi.
Dinas Kesehatan Kota Medan, lewat jawaban tertulis, menyatakan cakupan imunisasi di Kota Medan per Juni 2025; yaitu Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan sasaran 32.490 anak hanya mencapai 6.184 (19,03%) dan Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) dengan sasaran 35.085 anak, mencapai 5.051 (14,40%).
Fenomena penolakan dan rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia, khususnya Sumatra Utara turut dijelaskan oleh Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU, Destanul Aulia. Ia yang juga seorang pemerhati kesehatan, memandang hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari sisi masyarakat (demand side) dan dari sisi penyedia (supply side).
“Pemahaman masyarakat masih rendah, jadi masih banyak orang tua yang belum begitu mengerti tentang imunisasi. Kadang masih termakan isu-isu mitos dan hoaks,” ujarnya melalui wawancara daring, pada Selasa (22/7/2025).
Dampak pandemi Covid-19 juga ikut menjadi alasan cakupan imunisasi sempat turun, karena masyarakat takut datang ke Puskesmas. Di sisi lain, alasan ekonomi menjadikan keluarga tak menganggap imunisasi sebagai prioritas.
“Mengantar anak untuk melakukan imunisasi itu perlu akses, jarak, dan jam kerja. Jadi orang yang ekonominya sulit, dia harus rela tidak bekerja pada hari itu untuk mengantar anaknya imunisasi,” ucap Destanul.
Peduli dengan Herd Immunity
Kepala lingkungan V di kawasan rel kereta api tersebut, Evi Suwarno, menyatakan masyarakat sudah paham tentang imunisasi. Tapi tetap saja, masih kurang minat membawa anaknya ke Posyandu. Tiap pelaksanaan imunisasi, hadir 5 kader Posyandu, 1 dokter, dan 2 petugas untuk konsultasi pasien.
Mereka sediakan vaksin dari 0 bulan–5 tahun, terdiri dari suntik DPT dan Polio. Namun, lagi-lagi penolakan terhadap imunisasi pasal rasa cemas akan demam. “Stigma mereka itu begitu, tiap imunisasi ada aja keluhannya yang demam lah, yang mencret lah. Padahal itu kan normal,” ungkap Evi.
“Kalau mereka mengeluh ‘anak saya demam nggak bisa imunisasi’, tetap disuruh datang. Biar dijelaskan sama dokter, mereka biasanya bisa lebih menerima,” tutur Evi kembali.
Warga pun bebas memilih bawa anaknya ke Posyandu mana saja, terpenting bawa Kartu Keluarga (KK). “Walaupun dia warga luar tetap kita terima. Siapa aja ibu yang bawa anak akan dilayani,” tuturnya.

Seperti yang sebelumnya disebutkan, Destanul juga menyinggung dari sisi penyedia, masih ada beban untuk beberapa tenaga kesehatan. “Kadang stok vaksin tidak selalu lancar, data sasaran anak yang mau diberikan imunisasi belum tepat dan akurat, sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal,” keluhnya.
Program imunisasi memang menitikberatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, khususnya di daerah rel kereta api. “Ekonomi rendah, tempat tinggalnya berisiko. Kalau misalnya sebagian besar orang dalam komunitas tersebut sudah terlindungi, maka penularan penyakit bisa ditekan,” terang Destanul.
Ia menjelaskan ini lewat teori epidemiologi. Cakupan imunisasi yang rendah jadi ambang herd immunity tidak tercapai. Penyakit seperti campak dan polio, bisa menular dan menjadi wabah.
“Di komunitas padat, kontak antar individu sangat dekat sehingga penyebaran penyakit sangat cepat. Ditambah risiko tinggi karena lingkungan yang kurang sehat dan sanitasi yang tidak memadai,” tambahnya.
Pendekatan One Health adalah kunci
Jika cakupan imunisasi masih rendah, walhasil kualitas kesehatan anak-anak akan terdampak, yang bisa sebabkan morbiditas, bahkan kematian atau mortalitas. Ini bukan masalah individu, apabila terus terjadi maka daya tahan komunitas secara keseluruhan akan melemah.
“Dari sisi ekonomi kesehatan, namanya eksternalitas. Kalau masih ada masyarakat yang belum mendapat imunisasi, maka akan memengaruhi kesehatan yang lainnya,” ucap Destanul.
Pendekatan sosial-budaya menjadi akar dalam terlaksananya program imunisasi, terutama di kawasan padat seperti pinggir rel. Petugas kesehatan tidak cukup hanya memberi vaksin, mereka juga harus bangun kedekatan dan kepercayaan. “Keputusan imunisasi sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai budaya, dan norma di komunitas,” ujarnya.
“Kalau petugas tidak memahami cara komunikasi yang sesuai budaya lokal, pesan kesehatan bisa ditolak,” imbuh Destanul.
Peran tokoh adat dan agama pun jadi penting sebagai jembatan informasi. Model pemaksaan massal seperti dulu tak lagi ampuh di era informasi terbuka. Artinya, kesadaran harus dibangun, bukan dipaksakan.
Semua anak, di mana pun ia tinggal, berhak untuk sehat. Masyarakat pun perlu paham soal siklus hidup, bahwa masa bayi dan remaja adalah fase krusial. “Jika anak tidak terlindungi di usia dini, dampaknya bisa jangka panjang, baik secara fisik maupun kecerdasan,” tegasnya.
Undang-Undang No. 17 tahun 2023, wajib disematkan dalam peran petugas kesehatan saat turun ke lapangan. Gunakan cara komunikasi yang masyarakat pahami, jadi langkah pertama untuk yakinkan mereka tentang hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Menyisir program imunisasi di kawasan padat penduduk seperti pinggiran rel kereta api, harus memantik kolaborasi antar semua pihak. Ini bukan lagi soalan tanggung jawab pemerintah saja. “Tapi juga tanggung jawab Dinas Pendidikan, Dinas Agama, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Kita harus sama-sama mewujudkan pendekatan One Health,” tandas Destanul.
*****
Tulisan ini bagian dari program pelatihan dan beasiswa “Menguatkan Kesadaran Publik tentang Imunisasi” yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Global Health Strategies (GHS).