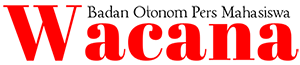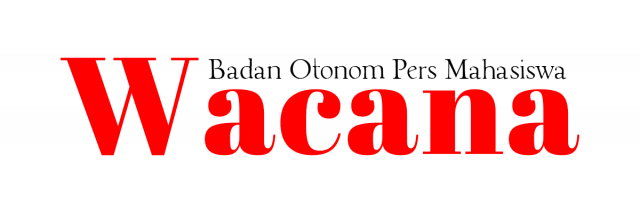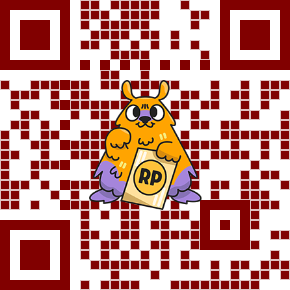Oleh: Muhammad Rifqy Ramadhan Lubis
Ketika sejarah disusun tanpa menyertakan luka, maka sesungguhnya yang dibangun bukanlah narasi bangsa, melainkan sebuah propaganda
Wacana terhadap Revisi Sejarah Nasional Indonesia (SNI) tengah digaungkan oleh pemerintah saat ini. Melalui Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon, sudah berkoordinasi dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) untuk menulis ulang naskah SNI dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kendati demikian, alih-alih penulisan naskah dapat lebih objektif dan eksplisit dalam menggambarkan sejarah terdahulu, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataannya.
Dilansir dari media Tempo, dikatakan bahwa pemerintah hendak melakukan revisi terhadap naskah SNI, tetapi peristiwa yang mencantumkan kasus pelanggaran HAM berat tidak dimuat dalam draf awal tersebut. Tentu hal ini menimbulkan kontradiktif bagi beberapa kalangan sejarawan. Bagaimana tidak? Apabila narasi yang tertulis akan mengarah pada media propaganda dalam legitimasi kekuasaan, maka yang terjadi hanyalah indoktrinasi anak bangsa yang buta akan sejarahnya.
Penyelenggaraannya pun dilakukan secara tertutup dan dikebut pada rapat kerja bersama Komisi X DPR per 12 Mei 2025 lalu. Hal semacam itu dapat dinilai mencederai keterbukaan dan keadilan dalam objektivitas penulisan sejarah. Penghapusan atau pengaburan peristiwa gelap hanya demi menjaga citra negara ini, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai sejarah itu sendiri.
Sejarah bukan media propaganda pemerintah
Narasi sejarah yang berdasarkan objektivitas baik dari kemenangan ataupun kekalahan, kebanggaan maupun kesalahan, tentu dapat menjadi ruang berpikir kritis. Seharusnya pemerintah lebih progresif dalam menyajikan kebenaran tentang masa lampau, agar melatih anak-anak bangsa ini berpikir cermat dalam mengkaji dan memahami narasi sejarah yang dipaparkan.
Daripada memilih mengabadikan kisah kejayaan sembari menyembunyikan tragedi-tragedi seperti Pembantaian 1965, Operasi militer di Timor-Timur, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Tragedi Talangsari 1989, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan aktivis 1997/1998, serta berbagai rentetan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orba.
Seharusnya negara memahami bahwa pengingkaran terhadap kebenaran merupakan suatu bentuk simbolik penghinaan terhadap para korban. Semboyan tentang “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” kini seperti bualan belaka, karena negara tidak pernah mau belajar dari luka bangsanya.
Yang kita butuhkan dalam revisi SNI bukanlah sebuah manipulasi sejarah melainkan pendidikan sejarah. Menghapus peristiwa kelam dari SNI sama saja dengan mematikan nalar berpikir kritis generasi bangsa ke depannya. Bayangkan saja, ribuan siswa membaca sejarah bangsanya tanpa pernah tahu bahwa negara ini pernah menyaksikan penghilangan paksa, penyiksaan, pengusiran, serta kekerasan sistemik yang dilegalkan atas nama keamanan dan kestabilan nasional.
Hak para korban untuk diakui
Para korban bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga kehilangan hak-haknya dalam ingatan memori kolektif bangsa. Ini bukan hanya tentang persoalan nilai moral, tetapi juga mandat konstitusional yang harus ditegakkan. Negara sudah mengatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwasanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang seharusnya tidak dibenarkan, apalagi dihapus dalam peradaban.
Chang Yau Hoon, seorang Profesor Antropologi dari Universitas Brunei Darussalam, melalui wawancaranya kepada beberapa pejabat Indonesia kala itu terkhususnya Fadli Zon menyebutkan bahwa, beberapa diantara mereka menyangkal adanya pemerkosaan massal yang terjadi pada tragedi 1998. Pengingkaran peristiwa kelam yang dilakukan tentu menjadi bukti bagaimana sejarah bisa dipolitisasi oleh mereka yang berkuasa.
Revisi SNI yang dipimpin oleh sosok yang menyangkal adanya tragedi tersebut tentu menjadi alasan adanya upaya penghapusan serta merekayasa ulang peristiwa sejarah yang sarat akan kepentingan. Selain itu, pengingkaran terhadap masa lalu dan narasi yang bersifat subjektif, memberikan kecemasan tersendiri terhadap mereka yang merasa dikhianati oleh negaranya sendiri, terkhusus para keluarga korban.
Tetapi, di tengah kerisauan tersebut, Aksi Kamisan hadir sebagai simbol perlawanan terhadap amnesia negara. Aksi Kamisan, yang kini telah memasuki tahun ke-18, bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah simbol perlawanan terhadap negara yang bisu, sebuah pengingat kolektif bahwa sejarah pelanggaran HAM di Indonesia belum selesai.
Aksi ini adalah suara dari para korban dan keluarga korban. Ia menolak lupa, menolak diam, dan menolak tunduk pada narasi sejarah yang dibersihkan dari luka. Ironisnya, negara yang selama hampir dua dekade mendengar seruan mereka, justru memilih menyingkirkan suara-suara itu dalam draf revisi SNI. Negara ingin menulis sejarahnya sendiri, sejarah yang tidak menyakitkan, tidak mengusik, dan tidak memalukan.
Torehan luka dalam sejarah tidak perlu dilupa
Dalam banyak negara, sejarah kelam justru menjadi titik tolak pembelajaran yang penting. Jerman mengakui Holocaust, Belanda meminta maaf atas kolonialisme yang mereka lakukan, Amerika menghapus perbudakan yang sudah lama terbangun. Langkah pemerintah untuk tidak mencantumkan peristiwa pelanggaran HAM dalam sejarah nasional menunjukkan bahwa negara lebih takut terhadap masa lalunya sendiri ketimbang berani memperbaikinya.
Penghapusan bukan hanya terjadi dalam isi, tetapi juga dalam cara bercerita. Bahasa menjadi senjata baru. Dengan menyebut masa represif sebagai “gejolak” dan menyematkan label “ancaman terhadap integrasi”, negara menciptakan narasi yang seolah netral, padahal sesungguhnya sarat kepentingan. Ini adalah bentuk baru dari pelurusan sejarah yang tidak jujur.
Ketika istilah seperti “Orde Baru” atau “Orde Lama” dihapus atau diganti, seolah negara sedang mencuci tangan atas sejarah kekerasan struktural yang berlangsung puluhan tahun. Maka kita harus waspada: perubahan istilah adalah awal dari perubahan makna. Perubahan makna dapat mengaburkan siapa korban dan siapa pelaku. Dalam proses revisi ini, negara bukan hanya sedang menulis ulang sejarah, tetapi juga sedang menentukan siapa yang layak diingat, dan siapa yang dilenyapkan dari buku pelajaran.
Ini mengingatkan pada gagasan yang diusung oleh Leopold von Ranke, sejarawan Jerman yang dianggap sebagai bapak historiografi modern. Ranke menekankan bahwa sejarah harus ditulis “wie es eigentlich gewesen” (sebagaimana adanya). Teori hukum dalam sejarah menyebutkan bahwa penulisan sejarah tidak boleh diubah sedikit pun karena dapat mengubah pemahaman dan transkrip sejarah itu sendiri.
Revisi sejarah nasional yang menghapus kekerasan, penghilangan paksa, dan luka kolektif adalah ancaman bukan hanya terhadap kebenaran, tapi terhadap demokrasi itu sendiri. Hanya bangsa yang berani mengakui lukanya yang bisa benar-benar sembuh dan tumbuh.
Maka, suara-suara dari jalanan yang menuntut keadilan, dari buku-buku yang dilarang, dari air mata para ibu yang kehilangan, semua itu harus lebih lantang. Dalam dunia yang sedang bergegas untuk melupakan, mengingat adalah tindakan perlawanan. Dan sejarah, selamanya, adalah milik mereka yang berani mengingat.